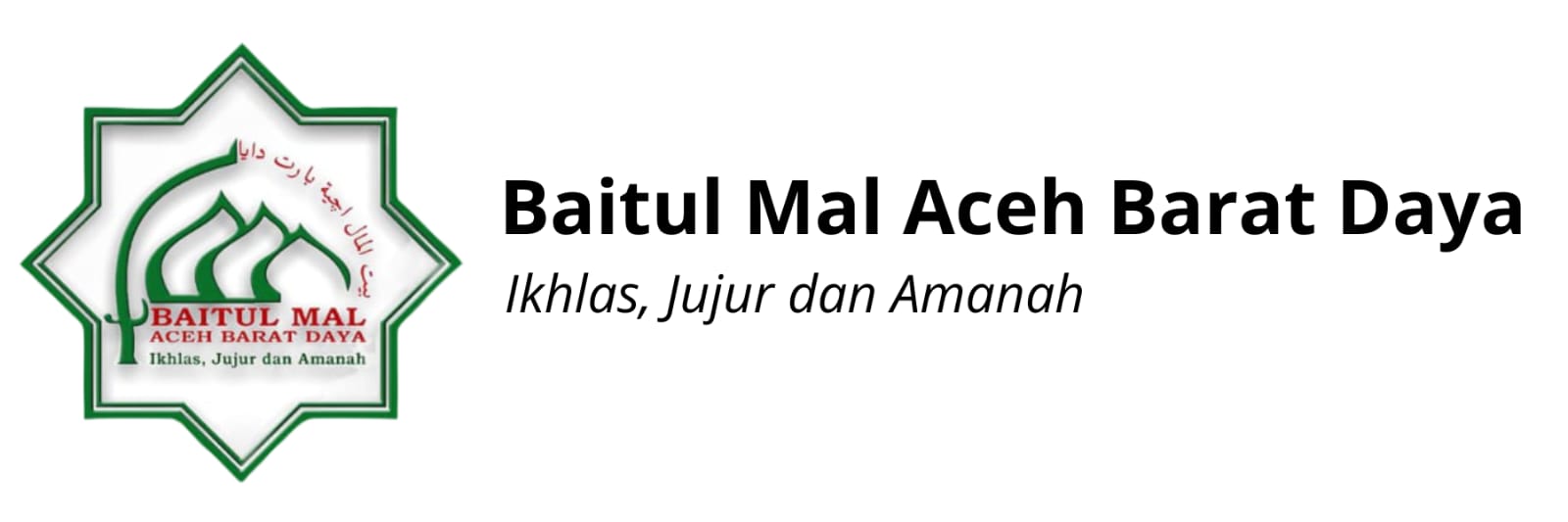Oleh: Muhammad Ikbal Fanika
ZAKAT bukan sekadar kewajiban ritual tahunan, ia adalah instrumen sosial-ekonomi yang dirancang langsung oleh Allah SWT untuk menegakkan keadilan, membersihkan harta, dan menumbuhkan solidaritas di tengah masyarakat.
Dalam Al-Qur’an, perintah zakat berdampingan dengan perintah shalat, hal ini menunjukkan betapa zakat bukan hanya urusan finansial, tetapi ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial.
Bagi seorang Muslim, zakat adalah tanda kepatuhan kepada Allah SWT. Ia membersihkan hati dari sifat kikir, mengingatkan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103). Dengan demikian, motif pertama berzakat adalah bentuk penghambaan kepada Allah, bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya.
Namun, zakat bukan hanya menyucikan harta muzaki (pemberi zakat), tetapi juga menyucikan tatanan sosial. Ia hadir untuk meruntuhkan sekat antara si kaya dan si miskin, membangun rasa persaudaraan, serta menutup celah kesenjangan yang kerap melahirkan konflik dan kecemburuan sosial.
Sejarah mencatat, zakat mampu menjadi solusi nyata dalam menghapus kemiskinan. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (seorang khalifah Bani Umayyah yang terkenal adil) diriwayatkan hampir tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Para amil baitul mal bahkan kesulitan mencari mustahik, karena kemakmuran merata.
Kebijakan Umar bin Abdul Aziz sederhana tapi mendalam. Ia menegakkan keadilan distribusi, memastikan zakat benar-benar sampai pada yang berhak, dan tidak menumpuk di kas negara. Ia juga mendorong pengelolaan zakat untuk pembangunan ekonomi, sehingga mustahik tidak hanya diberi ikan, tetapi juga kail. Dengan begitu, orang miskin bangkit menjadi mandiri, dan masyarakat luas menikmati kesejahteraan.
Kisah ini bukan dongeng utopis. Ia adalah bukti sejarah bahwa zakat, jika dikelola amanah, adil, dan strategis, mampu menghapus kemiskinan struktural.
Di zaman modern, peran baitul mal sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus meneladani spirit Umar bin Abdul Aziz. Baitul mal bukan sekadar lembaga yang menyalurkan bantuan atau santunan sesaat. Memang, santunan tetap penting untuk keadaan darurat, seperti anak yatim, keluarga dhuafa, atau korban bencana. Namun, bila hanya berhenti di sana, zakat akan habis sebagai konsumsi sesaat, tanpa dampak jangka panjang.
Baitul mal seharusnya hadir dengan strategi pemberdayaan. Bayangkan seorang petani miskin yang sebelumnya menerima santunan beras setiap bulan. Jika baitul mal membimbingnya, memberikan modal usaha tani, mendampingi dengan pelatihan, serta menghubungkannya ke pasar, maka petani itu lambat laun akan bangkit. Dari mustahik (penerima zakat), ia akan berubah menjadi muzaki (pemberi zakat).
Cita-cita besar pengelolaan zakat adalah mengurangi jumlah mustahik dan mencetak sebanyak-banyaknya muzaki. Inilah visi yang akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Sebab, masyarakat yang ekonominya kuat akan lebih tenang dalam beribadah, lebih fokus pada pendidikan anak, dan lebih mudah menebarkan kebaikan.
Selain kewajiban spiritual, zakat juga menumbuhkan kesadaran bahwa harta memiliki fungsi sosial. Harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Dengan berzakat, seorang Muslim sejatinya sedang membangun benteng sosial. Ia membantu tetangga miskin agar tidak lapar, mendukung anak yatim agar bisa bersekolah, dan meringankan beban keluarga yang kesulitan berobat. Maka, zakat adalah bentuk nyata dari ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) sekaligus solidaritas kemanusiaan.
Namun, semua potensi zakat akan sia-sia jika pengelolanya tidak amanah. Para amil zakat memegang kunci penting dalam transformasi sosial-ekonomi umat. Mereka harus profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola dana umat.
Amil zakat bukan sekadar “penyalur bantuan”, tetapi manajer dana sosial umat yang harus piawai menyusun program. Mereka wajib memiliki kompetensi dalam perencanaan, manajemen keuangan, pendampingan masyarakat, hingga monitoring dampak program.
Program zakat tidak boleh berhenti pada pola konsumtif (santunan sembako, uang tunai), tetapi harus dirancang berlapis, mulai program jangka pendek pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, kesehatan), jangka menengah pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendampingan, serta jangka panjang membentuk ekosistem ekonomi umat yang mandiri, misalnya koperasi syariah, UMKM berbasis komunitas, dan penguatan sektor pertanian atau perikanan.Dengan amil yang amanah dan profesional, zakat akan menjadi energi sosial yang luar biasa besar.
Bayangkan, jika setiap mustahik yang menerima zakat hari ini, dalam lima tahun ke depan bisa berubah menjadi muzaki karena berhasil diberdayakan. Maka, jumlah orang miskin berkurang, basis ekonomi umat semakin kuat, dan distribusi zakat semakin meluas.
Inilah tujuan zakat yang sejati, bukan sekadar mengurangi penderitaan sesaat, melainkan menciptakan siklus keberkahan. Muzaki membantu mustahik, mustahik bangkit menjadi muzaki, dan lingkaran kebaikan terus berputar.
Kondisi ideal inilah yang harus dikejar. Seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika penerima zakat sulit ditemukan, bukan karena zakat dihentikan, tetapi karena masyarakat telah sejahtera.
Sekali lagi, motif berzakat sejatinya mencakup tiga dimensi, ketaatan kepada Allah, penyucian harta, dan tanggung jawab sosial. Zakat adalah pilar ekonomi Islam yang, jika dikelola dengan baik, mampu menghapus kemiskinan, memperkuat solidaritas, dan memberdayakan umat.
Baitul mal sebagai lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar. Tidak hanya berperan sebagai penyalur santunan, tetapi merancang strategi pemberdayaan jangka panjang agar masyarakat miskin bangkit menjadi mandiri. Dengan demikian, cita-cita “menghilangkan mustahik dan mencetak muzaki” bukan sekadar utopia, melainkan target realistis yang bisa diwujudkan.
Tentu, syaratnya adalah para amil zakat harus amanah, profesional, dan inovatif. Mereka harus memahami bahwa zakat bukan dana seremonial, melainkan investasi sosial untuk membangun generasi sejahtera.
Semoga dengan semangat ini, masyarakat kita semakin makmur, hidup dalam kedamaian, dan mampu menunaikan ibadah dengan tenang. Sebab, bangsa yang kuat lahir dari keadilan ekonomi, dan zakat adalah instrumen utama yang diwariskan syariat Islam untuk mewujudkannya. []
Penulis adalah Dosen KPI FDK UIN Ar-Raniry, dan Dewan Pengawas BMK Aceh Barat Daya.